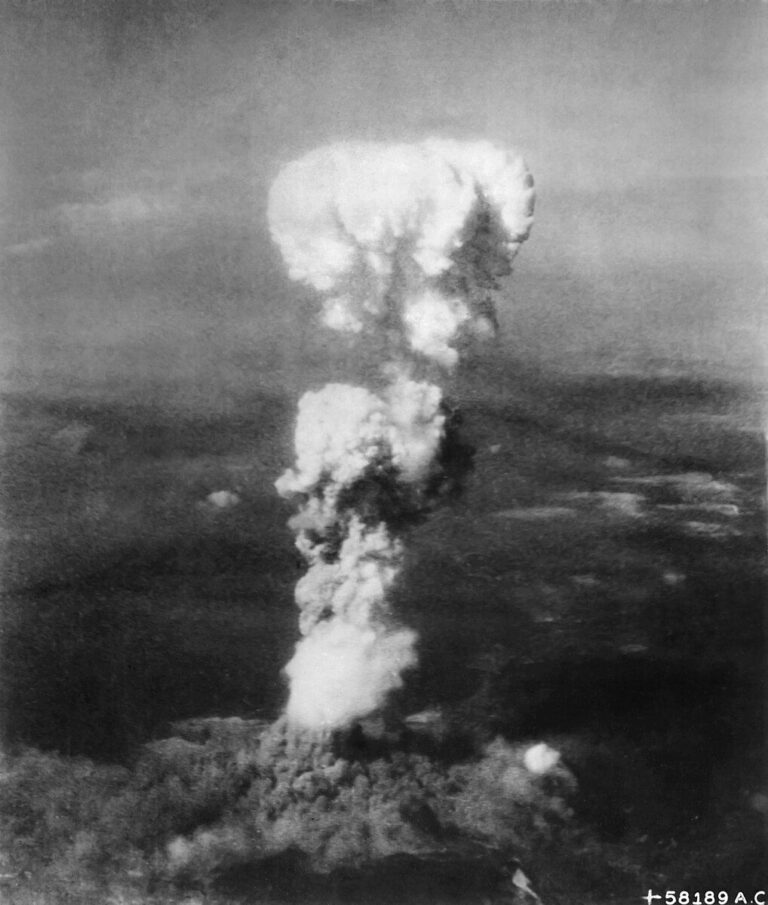Sejarah Panjang Konflik Aceh dan Perjanjian Helsinki
Perang yang berlangsung selama bertahun-tahun di Aceh akhirnya berakhir melalui kesepakatan yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini dikenal sebagai Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menjadi titik akhir dari konflik bersenjata yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade.
Perjanjian tersebut difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, dan menjadi langkah penting dalam menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi yang muncul akibat operasi militer dan korban jiwa yang signifikan. MoU ini tidak hanya mengakhiri kekerasan, tetapi juga memberikan dasar untuk otonomi khusus bagi Aceh.
Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah penarikan pasukan non-organik TNI/Polri, pelucutan senjata GAM, serta pemberian amnesti kepada mantan kombatan. Selain itu, Aceh diberikan hak untuk membentuk partai politik lokal, yang menjadi bagian dari otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Akar Masalah Konflik Aceh
Sofyan Djalil, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, mengungkapkan bahwa akar masalah konflik Aceh bisa dilihat sejak 1953 ketika daerah tersebut digabungkan ke Sumatera Utara. Ia menjelaskan bahwa Aceh memiliki sejarah dan status yang berbeda, namun penggabungan tersebut dinilai tidak adil dan tidak memperhatikan faktor sejarah serta perasaan masyarakat setempat.
Penggabungan ini menciptakan rasa tidak puas yang akhirnya meletup menjadi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah kepemimpinan Daud Beureu’eh. Konflik ini akhirnya diselesaikan dengan pemberian status daerah istimewa, yang memberi kewenangan khusus di bidang agama, pendidikan, dan adat.
Gelombang Baru Perlawanan
Seiring waktu, gelombang baru perlawanan muncul pada 1976 setelah ditemukannya ladang gas besar di Arun. Masyarakat Aceh merasa tidak ikut menikmati hasilnya, sehingga Hasan Tiro mendirikan GAM. GAM tidak hanya merekrut pasukan bersenjata, tetapi juga kalangan sarjana, dokter, dan insinyur.
Pemerintah Orde Baru merespons dengan operasi militer yang mengubah Aceh menjadi daerah operasi militer (DOM). Hal ini memicu pelanggaran hak asasi manusia yang semakin luas. Menurut Tengku Kamaruzzaman, mantan negosiator GAM, empat fondasi masalah utama adalah korupsi sistemik, pemerintahan yang sangat tersentralisasi di Jakarta, tekanan militer, dan aspirasi politik Aceh yang berbeda dengan pusat.
Upaya Damai dan Peran Bencana Tsunami
Setelah reformasi, pemerintah mencoba jalur damai. Pada 2002, perjanjian Cessation of Hostilities Agreement (COHA) gagal bertahan karena GAM memanfaatkan gencatan senjata untuk memperkuat diri. Pada era Presiden Megawati, darurat militer kembali diberlakukan, meskipun secara militer pemerintah unggul, GAM sulit dilumpuhkan karena kepemimpinan mereka berada di luar negeri.
Menurut Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM, upaya damai sudah dimulai jauh sebelum bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Ia menyebut bahwa diskusi tentang Aceh sudah dilakukan sejak Februari 2002. Tsunami menjadi katalis perdamaian karena kedua pihak sama-sama kehilangan orang dan peralatan.
Melalui perantara Juha Christensen, pemerintah dan GAM sepakat berunding di Helsinki awal 2005. Martti Ahtisaari memfasilitasi enam putaran negosiasi. Prinsip utama pemerintah adalah tidak ada kemerdekaan, tetapi Aceh bebas mengajukan tuntutan lain.
Hasil Diplomasi dan Keberhasilan Perjanjian
Bagi Sofyan Djalil, MoU Helsinki adalah hasil diplomasi kreatif, dukungan penuh presiden dan TNI, serta goodwill kedua pihak. Ia menilai bahwa kesepakatan ini merupakan kombinasi dari momentum tepat dan kelelahan berperang. Perjanjian ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan Aceh.